|
 |
||||||||||
|
Penulis: Sapardi
Djoko Damono
Pada acara Temu
Mitra Redaksi Mizan Pustaka yang bertema Menjelajah Sastra Terjemahan, yang berlangsung di Bandung, 8 Februari 2003 Sapardi
Djoko Damono, Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia menyampaikan pandangannya tentang tema itu. Bagaimana pandangan
Sapardi tentang hal itu, Mizan Online menyajikan untuk Anda.
Karya sastra adalah
hasil kerja sastrawan, tidak begitu saja jatuh dari langit. Sastrawan adalah manusia, anggota masyarakat yang menyadari perlunya
berkomunikasi dengan manusia lain; dengan demikian sastra memerlukan pembaca. Di dalamnya, sastrawan berusaha menciptakan
dunia rekaan berdasarkan kemampuan daya khayalnya. Dunia rekaan itu tentu saja harus bisa dikenal pembaca, sebab jika tidak,
komunikasi tidak akan berlangsung. Pembaca, seperti halnya sastrawan, adalah juga manusia, anggota masyarakat yang tentunya
juga menyadari pentingnya berkomunikasi. Di dalam proses komunikasi semacam itu sastrawan adalah pengirim pesan, sedangkan
pembaca adalah penerima pesan. Karya sastra adalah pesan itu, yakni dunia rekaan yang isinya harus dikenal baik oleh sastrawan
dan masih bisa dikenal pembaca agar komunikasi bisa berlangsung. Dalam proses tersebut
tampaknya pembaca adalah penerima yang pasif sedangkan sastrawan pengirim pesan yang aktif; kenyataannya tidaklah demikian.
Karya sastra modern, yang tertulis, pada dasarnya merupakan susunan huruf, kata, kalimat, dan alinea yang bisa menjelma dunia
hanya jika pembaca secara aktif menafsirkannya; ia menjadi "sastra" dan menjelma sebuah dunia hanya jika diciptakan kembali
oleh pembaca. Jika tidak, ia mungkin merupakan kertas bertulisan yang bisa saja menjadi bungkus kacang. Ada atau tidaknya
karya sastra sama sekali bergantung pada pembaca yang menjadi juru tafsir, dan dalam hal ini tentu saja sastrawan bisa juga
menjadi pembaca karyanya sendiri. Dalam proses menafsirkan itulah sebenarnya terjadi komunikasi langsung antara karya sastra
dan pembaca, atau komunikasi tak langsung antara sastrawan dan pembaca. Sebagai manusia, sastrawan
tidak bisa melepaskan diri dari dunia tempatnya berpijak. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari gagasan, tindak-tanduk, dan
benda-benda√Ę‚¨‚Ěyakni kebudayaan√Ę‚¨‚Ěyang dihasilkan manusia; ia pun ikut menghasilkan itu semua. Jadi, sastrawan adalah
bagian kebudayaan dan sekaligus ikut menghasilkan kebudayaan. Tentu saja karya yang diciptakannya, yakni sastra, adalah dunia
yang tak bisa dipisahkan dari kebudayaannya. Sastra adalah dunia rekaan yang berpijak pada gagasan, tata nilai, dan kaidah
yang telah membentuk dan sekaligus dibentuk sastrawan sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, "berpijak" tentunya tidak
berarti "sama dan sebangun"; sastra adalah tanggapan evaluatif terhadap berbagai hal yang berlangsung di dunia nyata ini.
Dalam menilai, sastrawan menyodorkan pilihan-pilihan. Itu sebabnya juga sering dikatakan bahwa dunia rekaan adalah alternatif
bagi kehidupan kita sehari-hari. Orang membaca karya
sastra karena ia tidak ingin berada di dunia nyata yang satu-satunya ini, dan berusaha melarikan diri ke dunia yang berbeda,
yang diciptakan sastrawan. Ini tidak berarti bahwa ia berpindah ke dunia yang lebih nyaman; bisa saja dunia alternatif itu
malah "menyiksa"-nya. Bisa saja orang merasa sangat berbahagia di dunia sehari-harinya, namun masuk juga ia ke dunia sastra
yang mungkin malah membuatnya menangis, geram, atau penasaran. Orang mendapatkan juga pengalaman di dunia nyata ini, namun
dunia sastra, yang diciptakan oleh sastrawan entah sejak kapan, memberinya lebih banyak lagi pilihan pengalaman. Dengan demikian,
hakikat keberadaan sastra adalah niat baik pembaca untuk menerima pengalaman yang ditawarkan sastrawan. Dalam zaman modern
ini, dunia alternatif umumnya dikemas dalam bentuk buku. Dengan demikian sastra adalah dunia yang portable, bisa dijinjing
ke mana pun dan siap dimasuki sembarang waktu dan tempat. Tidak usah heran jika kita pernah menyaksikan orang membaca novel
di bus, pesawat terbang, kereta api, dapur, toilet, atau kamar belajar. Dunia jinjingan itu berisi kebudayaan, yakni gagasan,
nilai-nilai, dan kaidah-kaidah yang diciptakan kembali dan sekaligus dievaluasi oleh sastrawan. Tentu saja, seperti halnya
benda budaya lain, ada berbagai-bagai jenis sastra. Ada sastra yang menawarkan dunia yang sudah begitu kita kenal sehari-hari
dan mengajak kita untuk tetap mencintainya dan sama sekali tidak beranjak darinya; ada yang menantang kita untuk mempertimbangkan
kembali segala sesuatu yang selama ini kita yakini dan menggoda kita untuk merombaknya. Itu semua merupakan cerminan kebudayaan
yang telah melahirkannya. II Tentu karena kita
membutuhkannya maka sastra telah dihasilkan entah sejak kapan. Jika kita mengambil cara pandang ini begitu saja, seolah-olah
tidak ada gunanya memperbincangkan arah dan nasib sastra kita di masa datang; apa pun yang terjadi, sastra di mana pun pasti
akan dihasilkan. Yang perlu kita bicarakan sekarang adalah mengapa sastra harus ada dan untuk apa pula benda budaya itu ada.
Meskipun mungkin saja menjadi terharu atau bahkan menangis ketika membaca karya sastra, kita sepenuhnya menyadari bahwa yang
kita hadapi hanyalah gambaran dunia rekaan yang tidak akan mampu menyelesaikan kemelut yang terjadi dalam hidup kita. Ia tidak
nyata, sedangkan kesulitan hidup sehari-hari kita ini benar-benar nyata. Tetapi justru karena
sifat rekaannya itulah sastra kita butuhkan. Kita tidak mungkin tinggal terus-menerus di dunia nyata. Agar hidup ini bisa
terlaksana dan berlangsung dengan sebaik-baiknya, kita perlu mengadakan perjalanan ulang-alik dari dunia nyata ke dunia rekaan.
Setiap harinya kita, yang hidup sebagai anggota masyarakat modern ini, melakukan itu: nonton telenovela atau film seri di
televisi; membuat dan mendengarkan folklore, yakni cerita burung mengenai tetangga, kenalan, atau saudara; atau membaca
cerita bersambung atau cerita pendek yang dimuat di berbagai media massa. Dunia rekaan ternyata merupakan pasangan dunia nyata.
Jika di dunia nyata ini gerak-gerik kita ada rambu-rambunya, ada batas-batas yang sebenarnya kita ciptakan sendiri demi keinginan
bermasyarakat, maka di dunia rekaan kita mendapatkan keleluasaan yang memungkinkan kita melewati batas-batas itu. Di dalam dunia nyata,
apa yang terjadi tidak akan bisa diulang lagi. Menurut teori mimesis, di dalam dunia rekaan itu apa yang terjadi di dunia
nyata bisa "diulang" lagi; dan dunia "ulangan" itu bisa terus-menerus diulang-ulang setiap kali kita membacanya. Dengan demikian
ia merupakan semacam cermin dari segala sesuatu yang menimpa diri kita ini; menghasilkan sastra berarti menyaksikan diri kita
sendiri bermain di suatu dunia rekaan. Karena cermin itu meniru apa yang dicerminkannya, maka sastra pada dasarnya dianggap
sebagai mimesis. Namun, dalam hal ini mimesis adalah tiruan yang juga memperbaiki kekurangan yang ada pada yang ditiru. Sastra
adalah cermin yang istimewa, ia tidak hanya menampilkan diri kita seperti yang ada di dunia nyata, tetapi sekaligus memperbaikinya.
Ini berarti sastra juga menampilkan hal yang tidak tampak dalam dunia nyata, hal yang tidak bisa diketahui dalam dunia nyata. Dengan cara lain bisa
dikatakan bahwa sastra merupakan tanggapan evaluatif terhadap kehidupan; sebagai semacam cermin, sastra memantulkan kehidupan
setelah menilai dan memperbaikinya. Kita menciptakan sastra sebab membutuhkan citraan rekaan yang bisa mencerminkan hal yang
tidak kita ketahui di dunia nyata. Itulah sebabnya, setidaknya menurut Wolfgang Iser,2 sastra tidak tergusur oleh perkembangan
filsafat sejarah dan teori sosiologi, yang juga merupakan cermin diri kita, sebab sastra pada dasarnya justru mencerminkan
yang tidak ada. Sastra menghadirkan yang tidak hadir, mementaskan yang tidak terpentaskan dalam kenyataan sehari-hari. Pertanyaan
yang penting adalah, mengapa gerangan kita menciptakan cara pementasan semacam itu, yang telah bersama kita sepanjang sejarah
yang kita catat selama ini? Jika kita mengikuti
jalan pikiran Iser, jawaban terhadap pertanyaan itu tentulah bukan sekedar keinginan untuk mengulang-ulang apa yang ada, tetapi
kehendak kuat untuk mendapatkan jalan masuk ke sesuatu yang tidak dapat kita ketahui. Kehendak itulah yang menyebabkan sastra
tetap akan kita hasilkan dan tidak bisa digantikan oleh bidang lain apa pun. Dan tentunya buku-buku sastra tetap akan ditulis,
dicetak, dan disebarluaskan lewat berbagai-bagai saluran. III Di zaman ini, kita
menjumpai begitu banyak dunia jinjingan yang ditawarkan oleh sastrawan-sastrawan kita sendiri maupun asing. Kalau mau, kita
bisa masuk ke dunia Sitti Nurbaya, yang diterbitkan tahun 20-an ciptaan Mh. Rusli, seorang Minang; atau ke dunia Para
Priyayi yang diciptakan oleh Umar Kayam, seorang Jawa. Dr. Zhivago karya Boris Pasternak, orang Rusia; Malam
karya Eli Wiesel, orang Yahudi; Yang Tergusur karya Sally Morgan, orang aborigin Australia; Tukang Kebun karya
Rabindranath Tagore, orang India; Senandung Ombak karya Yukio Mishima, orang Jepang; Nyanyian Lawino karya Okot
p√Ę‚¨‚ĘBitek, orang Uganda; Tokoh-tokoh Munafik karya Sionil Jose, orang Filipina; Istri untuk Putraku karya
Ali Ghalem dari Aljazair; Nyanyian Ombak karya Yukio Mishima dari Jepang; Lelaki Tua dan Laut karya Hemingway
dari Amerika; semua itu beberapa contoh saja dari begitu banyak dunia√Ę‚¨‚Ěyang mencerminkan kebudayaan, yang berisi pengalaman√Ę‚¨‚Ěyang
siap kita masuki. Dan jika kita bisa menguasai bahasa asing, ada lebih banyak lagi pilihan untuk kita tentu saja. Moga-moga saja kita
masih ingat, dan bersedia mengakui, bahwa umumnya perkenalan pertama kita dengan beberapa segi kebudayaan Rusia tidak melalui
sosiologi tetapi lewat cerita pendek dan drama Anton Chehov; perkenalan pertama kita dengan berbagai nuansa masalah sosial,
politik, dan budaya Rusia tidak lewat ceramah ilmiah tetapi lewat buku-buku Nikolay Gogol, Leo Tolstoy, dan Boris Pasternak.
Dan anehnya, kesan perkenalan pertama itu tidak mudah hilang; mungkin hal itu antara lain disebabkan√Ę‚¨‚Ěkata orang√Ę‚¨‚Ě
sastra itu memorable, cenderung lekat ke ingatan. Anehnya lagi, karya sastra adalah dunia pengalaman yang bisa dihayati
berulang kali, dan setiap kali merupakan pengalaman yang umumnya lebih bernilai, karena kita tentunya sudah menjadi lebih
kritis. Kita sepenuhnya tahu bahwa membaca ulang sebuah novel, misalnya, tidak jarang lebih mengasyikkan dibanding membaca
novel baru. Novel yang pernah kita baca sewaktu di sekolah menengah tentu memberikan pengalaman yang berbeda dengan ketika
kita baca tiga puluh tahun kemudian, ketika kita hampir punya cucu. Contoh beberapa novel
yang saya sebut itu menunjukkan bahwa setidaknya akhir-akhir ini kegiatan menerjemahkan karya sastra asing ke dalam bahasa
Indonesia terus dilaksanakan dan tampaknya meningkat. Ini membuktikan bahwa sebagai bangsa, kita mempunyai rasa ingin tahu
yang kuat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan dan pengalaman bangsa lain. Kita menyadari bahwa dalam zaman komunikasi
yang semakin laju ini, tidak ada manfaatnya sama sekali untuk menutup diri dengan hanya mengagumi dan melestarikan kebudayaan
dan pengalaman diri sendiri. Untuk bisa bergaul dengan bangsa lain dengan lebih percaya diri, kita perlu mengenal kebudayaan
dan pengalamannya. Dan dalam hal ini, sastra adalah semacam jalan pintas. Saya akan memberikan
sekedar contoh. Aljazair adalah sebuah negeri di Afrika Utara yang boleh dikatakan asing bagi kebanyakan kita. Novel Ali Ghalem,
Istri untuk Putraku, memberikan gambaran dan uraian yang sangat tajam mengenai beberapa segi kebudayaan dan pengalaman
bangsa itu. Lewat novel itu kita bisa mengenal tata cara perkawinan yang sama sekali asing bagi kita. Dalam novel itu juga
diungkapkan berbagai masalah sosial dan budaya yang menyangkut masyarakat lapisan bawah; bahkan secara tersirat muncul juga
masalah hubungan antara Aljazair dan Perancis, negeri Eropa yang pernah menguasainya. Beberapa adegan dalam novel itu digambarkan
begitu tajam sehingga sulit lepas dari ingatan kita, seperti misalnya adegan yang menggambarkan tradisi pemeriksaan keperawanan
bagi gadis yang akan nikah. Juga adegan malam pertama pengantin. Dalam karya Ali Ghalem itu kita juga menemukan berbagai segi
masalah pendidikan, hak wanita, dan hubungan-hubungan antaranggota keluarga dan antarkeluarga. Sehabis membaca novel
itu, kita merasa seolah-olah tahu sangat banyak mengenai masyarakat suatu negeri yang sebelumnya sama sekali asing. Kita menimbang-nimbang
berbagai hal yang sama dan tidak sama dengan dunia dan masyarakat kita sendiri. Kita menjadi lebih kaya. Bahkan tidak jarang
kita merasa menjadi orang yang tahu banyak mengenai sosiologi dan psikologi masyarakat dan orang Aljazair, tanpa pernah ikut
kuliah kedua ilmu itu. Memang tidak benar jika dikatakan kita telah menjadi pakar sosiologi dan psikologi masyarakat Aljazair
hanya dengan membaca sebuah novel, namun tidak keliru jika dikatakan bahwa kita telah memahami dan menghayati beberapa segi
dunia pengalaman orang Aljazair, lengkap dengan tanggapan si sastrawan terhadapnya. Novel Yang Tergusur,
yang ditulis oleh Sally Morgan, sastrawan keturunan Aborijin di Australia, memberikan gambaran dan "uraian" yang sangat tajam
mengenai perkembangan hubungan antarras dalam sejarah sosial Australia. Tokoh utama novel ini, seorang perempuan muda keturunan
Aborijin, baru menyadari identitas dirinya √Ę‚¨‚ yang selama ini disembunyikan oleh orang tua dan seluruh keluarganya √Ę‚¨‚
setelah ia dewasa. Orang tuanya ternyata lebih merasa tenteram dan terlindung dengan membohongi dirinya sendiri sebagai keturunan
India daripada mengakui sebagai pribumi, orang Aborijin. Dalam upaya mencari akar itulah perempuan muda tersebut mendapatkan
pengalaman dan pengetahuan mengenai hubungan antara pribumi dan pendatang kulit putih. Dan kita yang ikut "menyaksikan" petualangannya
ke dunia leluhurnya merasa banyak mengetahui berbagai segi sosiologi, antropologi, politik, dan budaya negeri itu. Dalam buku Religion
of Java, Clifford Geertz telah memberikan gambaran yang mungkin dianggap lengkap dan luas mengenai "permukaan" sebuah
masyarakat Jawa di sebuah kota kecil di Jawa Timur; sementara itu di dalam Para Priyayi Umar Kayam mengungkapkan beberapa
segi saja dari dunia dan pengalaman beberapa orang Jawa, namun Umar Kayam menyusup jauh ke bawah permukaannya. Dan Umar Kayam
sekaligus juga menyiratkan penilaian terhadapnya. Geertz adalah seorang sarjana asing sedangkan Umar Kayam adalah seorang
sastrawan kita yang berasal dari Jawa. Contoh lain menyangkut pengarang yang sama, yakni A.A. Navis. Dalam bukunya mengenai
adat Minangkabau, Alam Terkembang Menjadi Guru, A.A. Navis memberikan gambaran permukaan yang luas mengenai masyarakat
itu, sementara dalam cerpen "Robohnya Surau Kami" ia langsung masuk ke bawah permukaan untuk mengungkapkan inti masalah yang
ada dalam kehidupan orang Minang. Saya sama sekali tidak
bermaksud mengatakan bahwa dari karya sastra kita hanya bisa mendapatkan informasi mengenai berbagai hal. Sastra memang bisa
informatif, tetapi ia juga kreatif. Yang ditawarkannya tidak hanya informasi tetapi juga pengalaman estetis, pengalaman masuk
ke dalam keindahan yang disalurkan lewat bahasa. Ketrampilan pengarang mempergunakan bahasanya itulah bahkan yang kadang-kadang
membuat kita menganggap bahwa dunia rekaan itu lebih nyata dari dunia yang kita hidupi sehari-hari. Bahwa fiksi itu lebih
nyata dari fakta. Itulah sebabnya dengan mudah kita bisa terlibat secara emosional dengan peristiwa dan tokoh rekaan yang
ada dalam novel. Itulah juga sebabnya maka tidak jarang karya sastra dilarang beredar karena dianggap melakukan intervensi
ke dalam kehidupan nyata, itu pula sebabnya maka "ada" kuburan Sitti Nurbaya di Padang. IV Seperti yang tersirat
dalam uraian terdahulu, sastra tidak hanya berurusan dengan dunia pribadi sastrawan tetapi juga, dan pada dasarnya, berurusan
dengan dunia sosial, usaha manusia untuk menyesuaikan diri dalam dunia itu, dan sekaligus usahanya untuk senantiasa mengubahnya
sehingga menjadi hunian yang lebih baik. Sastra adalah usaha untuk menciptakan kembali dunia sosial itu: hubungan-hubungan
keluarga, politik, agama, dan sebagainya. Ia juga menggarisbawahi peranannya dalam keluarga dan lembaga-lembaga lain, mengungkapkan
konflik dan ketegangan antarkelompok dan antargolongan. Seperti halnya sosiologi, sastra sebenarnya berhubungan dengan tekstur
sosial, ekonomi, dan politik. Namun, setidaknya menurut keyakinan Alan Swingewood3, seorang sosiolog, sastra berbuat lebih
dari itu dengan mengatasi sekedar deskripsi dan analisis obyektif dan ilmiah, dan masuk menyusup ke bawah permukaan kehidupan
sosial untuk mengungkapkan cara-cara manusia menghayati masyarakatnya. Bahkan menurut seorang sosiolog lain, tanpa kesaksian
sastra, pengamat masyarakat tidak akan mampu melihat sebaik-baiknya masyarakat secara utuh. Dengan kata-kata Richard Hoggart,
"Without the full literary witness, the student of society will be blind to the fullness of a society√Ę‚¨‚Ęs life.."4 Sehubungan dengan
keinginan kita untuk terus-menerus meningkatkan taraf pergaulan kita dengan bangsa-bangsa lain, usaha untuk menerjemahkan
karya sastra asing patut mendapat pujian. Dengan membaca cerita pendek Yukio Mishima yang berjudul "Sepukku," misalnya, kita
tidak hanya mendapat gambaran obyektif dan ilmiah mengenai "upacara" bunuh diri dalam masyarakat Jepang, tetapi bisa menghayati
bagaimana hal itu berlangsung, lengkap dengan detil perasaan dan emosi yang menggerakkannya. Penghayatan itu perlu untuk pemahaman,
dan pada gilirannya pemahaman itu mutlak diperlukan bagi usaha pergaulan yang lebih baik. Namun, tentu saja
dalam usaha bergaul itu kita tidak hanya harus menerima; kita juga harus memberi. Masalahnya adalah apa yang bisa kita berikan
dan bagaimana memberikannya. Kita tentu saja bisa menawarkan karya sastra kita kepada bangsa lain, sebagai salah satu usaha
penting agar bangsa lain memahami dan menghayati dunia kita. Sayang bahwa tidak begitu saja sastra kita, yang ditulis dalam
bahasa Indonesia dan Daerah, kita sodorkan begitu saja. Bahasa-bahasa kita belum lagi menjadi alat komunikasi antarbangsa.
Sebagai perbandingan saya akan menyebut sastra modern Afrika. Banyak di antara sastra benua itu ditulis dalam bahasa-bahasa
bekas penjajah, bahasa-bahasa Barat yang diterima sebagai bahasa antarbangsa. Kita tidak usah heran bahwa beberapa sastrawan
benua itu segera mendapat perhatian dunia, kata lain untuk pemahaman dan penghayatan masyarakat dunia. Dan tentu saja kita
juga tidak usah iri jika salah seorang sastrawan Nigeria, Wole Soyinka, menerima hadiah Nobel untuk kesusastraan pada tahun
1986. Hadiah itu tentu saja bukan merupakan satu-satunya ukuran penilaian dan perhatian, namun setidaknya merupakan salah
satu ukuran itu. Selama ini Indonesia
sudah menghasilkan sangat banyak dunia jinjingan itu. Usaha untuk mempromosikan negeri kita ini lewat kebudayaan, mau tidak
mau harus ditunjang dengan usaha penerjemahan karya sastra kita secara terus-menerus dan profesional. Yang bisa kita tawarkan
tentu tidak hanya terbatas pada sastra modern, yang telah menghasilkan beberapa karya yang setaraf dengan yang dihasilkan
negeri lain yang disinggung sebelumnya, tetapi juga sastra daerah dan sastra klasik. Kita menyadari sepenuhnya bahwa dunia
kita tidak berawal kemarin sore, tetapi sejak ratusan atau ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum nenek-moyang kita menciptakan
Hang Tuah, Cindur Mato, Raden Panji, dan Sangkuriang. Dari dunia Barat kita mengenal karya-karya Homerus, William Shakespeare,
dan T.S. Eliot, yang mencakup jangka waktu ribuan tahun. Dari anak benua Asia Selatan kita mengenal Mahabharata sampai
dengan karya V.S. Naipaul., yang mencakup ribuan tahun. Haiku dan karya Yasunari Kawabata juga berjarak ratusan tahun; itu
pun kita kenal. Jadi, tentu sangat banyak yang bisa kita tawarkan kepada bangsa lain, agar mereka bisa juga menghayati kita;
agar dalam pergaulan antarbangsa itu berlaku kaidah "memberi dan menerima". Agar bangsa lain juga mempunyai kesempatan untuk
menghayati kita sebagai bangsa yang telah membentuk kebudayaannya selama ribuan tahun. V Mengenai kedua hal
itu ada baiknya kita membaca semacam kesimpulan yang ditarik oleh seorang pakar sastra Melayu klasik, Sir Richard Winstedt
dalam pengantarnya tentang sastra Melayu klasik, A History of Classical Malay Literature.5 Katanya "Any one who
surveys the field of Malay literature will be struck by the amazing abundance of its foreign flora and fauna and the rarity
of indigenous growth." Siapa pun yang mengamati taman sastra Melayu klasik akan dikejutkan oleh melimpahruahnya flora
dan fauna asing serta langkanya tanaman asli. Yang dimaksudkan Winstedt adalah bahwa sastra Melayu ternyata diperkaya oleh
pengaruh asing dan bahkan jarang sekali yang merupakan ciptaan asli, tidak saja dari segi tema tetapi juga bahasanya. Bahasa
Melayu diperkaya oleh kosakata dari bahasa-bahasa di Asia Barat, Tengah, dan Selatan; asal-usul beberapa pengarang awal sastra
Melayu di zaman lampau pun ada kaitannya dengan negeri-negeri tersebut. Kita pun bahkan sempat mengembangkan aksara Jawi dan
Pegon, yang berasal dari aksara Arab. Seperti halnya yang terjadi dalam bahasa Inggris, pengaruh asing itulah ternyata yang
telah memperkokoh bahasa Melayu. Kesimpulan yang bisa
ditarik dari gambaran tersebut adalah bahwa bangsa kita ini ternyata senantiasa terbuka terhadap pengaruh asing dan sama sekali
tidak menunjukkan sikap kawatir atau tendah diri menghadapinya. Bangsa kita bahkan sengaja mengambil anasir kebudayaan asing
tersebut dan mengembangkannya sesuai dengan keperluannya sendiri. Kita sekarang tentunya tidak akan mengatakan bahwa bangsa
kita telah kehilangan kebudayaannya, telah digusur dan dikuasai oleh kebudayaan asing. Kebudayaan mana pun di dunia ini mengalami
hal yang serupa. Kita mengetahui bahwa kebudayaan-kebudayaan Korea dan Jepang bersumber pada kebudayaan Cina, tetapi sekarang
kita dengan mudah bisa membedakan ketiga kebudayaan tersebut. Sastra serta aksara Jepang dan Korea klasik bersumber pada sastra
dan aksara Cina, namun ketiganya sekarang masing-masing mengembangkan sastra modern yang mau tidak mau telah bersinggungan
dengan sastra Barat. Dan jika kita berbicara mengenai sastra Inggris, misalnya, kita boleh menanyakan naskah drama Shakespeare
yang mana gerangan yang benar-benar asli? Yang saya contohkan
itu ada katannya dengan masa lalu, ketika jaringan komunikasi tidak secanggih masa kini. Di zaman sekarang ini tidak akan
mungkin suatu kebudayaan berkembang sendiri tanpa bersinggungan dengan kebudayaan lain. Kita memang harus mengakui bahwa kebudayaan
yang kuat memang cenderung mempengaruhi yang lebih lemah. Jika pendukung kebudayaan yang lebih lemah itu bersikap pasif, tentu
ada kemungkinan ia hanya mendapatkan yang diberikan sekedarnya saja. Jika ia bersikap aktif, ia bisa memilih segala sesuatu
yang terkandung dalam kebudayaan lain, yang bisa dimanfaatkannya untuk memperkaya dan memperkuat diri sendiri. Jadi, kita
jangan takut dan was-was terhadap kebudayaan asing, tetapi justru harus aktif mencari dan merebut kebudayaan asing yang kita
anggap baik dan bisa dimanfaatkan. Sampai di sini sebenarnya
kita berbicara mengenai sastra elit. Kitab-kitab yang pada zaman lampau itu disadur atau ditiru dari khasanah bangsa lain
bukanlah bacaan populer dalam pengertian kita sekarang ini. Hasil kebudayaan itu beredar di kalangan sangat terbatas, yakni
keraton atau pusat-pusat kebudayaan serta agama yang sama sekali jauh dari pengertian kita tentang khalayak ramai. Namun,
hasil pengambilalihan kebudayaan asing itu akhirnya turun ke rakyat banyak juga dalam bentuk yang bisa saja sama sekali berbeda,
disesuaikan dengan kekayaan budaya yang ada sebelumnya. Wayang yang mendasarkan kisah-kisahnya pada Mahabharata dan
Ramayana, misalnya, telah mengubah hasil budaya elit itu menjadi hasil kesenian yang bisa dinikmati rakyat banyak,
yang mencakup rakyat kecil sampai lapisan paling atas dalam masyarakat√Ę‚¨‚Ěmeskipun sama sekali tidak ada hubungannya dengan
pengertian massa. VI Sebenarnya, setiap
kali berbicara mengenai penyusupan atau pengaruh kesusastraan asing, kita berbicara mengenai apa yang disebut kebudayaan massa.
Kebudayaan massa adalah istilah kita untuk mass culture, istilah Inggris yang konon berasal dari bahasa Jerman Masse
dan Kultur. Kebudayaan massa sebenarnya merupakan istilah yang mengandung nada mengejek atau merendahkan; istilah ini
merupakan pasangan dari high culture, kebudayaan elit atau kebudayaan tinggi. Kebudayaan tinggi mengacu tidak hanya
ke berbagai jenis kesenian produk simbolik yang menjadi pilihan kaum elit terpelajar dalam masyarakat Barat, tetapi juga ke
segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pikiran dan perasaan kaum yang menjatuhkan pilihan atas jenis kesenian dan produk
simbolik tersebut. Mass
atau Masse mengacu ke mayoritas masyarakat Eropa yang tak terpelajar dan nonaristokratik, terutama sekali masyarakat
yang sekarang ini biasa kita sebut sebagai kelas menengah bawah, kelas pekerja, dan kaum miskin. Jadi, jika kebudayaan elit
dikaitkan dengan mereka yang "berbudaya," maka kebudayaan massa dianggap milik mayoritas masyarakat yang uncultured
atau unlettered "tak berbudaya"√Ę‚¨‚Ěini jelas mengandung ejekan dan sikap merendahkan. Massa mengandung pengertian
kelompok manusia yang tidak bisa dipilah-pilahkan, semacam kerumunan, yang di dalamnya tidak ada lagi individu. Kebudayaan
massa diciptakan semata-mata untuk konsumsi masyarakat serupa itu. Dalam
khasanah kritik kebudayaan Barat, berbagai istilah yang nadanya merendahkan telah dipergunakan untuk menggambarkan hasil kebudayaan
massa dan pendukungnya. Dalam tulisan Dwight Macdonald,6 misalnya, disebutkan bahwa pendukung kebudayaan massa disebut adultized
children √Ę‚¨ňanak-anak yang didewasakan√Ę‚¨‚Ę dan infantile adults √Ę‚¨ňorang dewasa yang kekanak-kenakan.√Ę‚¨‚Ę
Alasannya adalah karena anak-anak zaman sekarang ini menonton segala jenis acara televisi yang sebenarnya sama sekali tidak
disediakan untuk mereka, sementara orang-orang dewasa gemar membaca komik dan nonton film, terutama kartun, yang sebenarnya
dimaksudkan untuk anak-anak. Dalam keadaan semacam itu masyarakat mengalami perkembangan yang aneh: anak-anak menjadi sangat
cepat dewasa, tetapi pada batas tertentu orang dewasa tidak lagi bisa berkembang cita rasanya. Konsep ini ada kaitannya dengan
pengertian immature taste √Ę‚¨ňcita rasa yang belum dewasa√Ę‚¨‚Ę yang disebut oleh A. Kaplan untuk menggambarkan cita
rasa para pendukung kesenian populer.7 Jika boleh disimpulkan dengan meminjam istilah yang dipergunakan oleh Matthew Arnold
dalam Culture and Anarchy, kebudayaan elit itulah culture sedangkan kebudayaan massa itu tak lain merupakan
anarchy.8 Pada hakikatnya, yang
kita risaukan adalah kebudayaan massa ini yang, sebagai akibat dari semakin berkembangnya komunikasi, memang dalam kenyataanya
tidak mungkin kita hindari. Dalam pembicaraan sehari-hari dan dalam berbagai seminar, umumnya kita menunjuk televisi sebagai
penyebar utama kebudayaan massa itu; sesudahnya baru media massa cetak dan perangkat audio-visual lain. Gans, seorang pembela
kebudayaan massa, menyebut empat hal utama yang menyebabkan kerisauan kita itu. Saya akan mencoba menafsirkannya dengan sesekali
mengacu ke berbagai gagasan lain yang ada kaitannya. Pertama, kita risau
terhadap kebudayaan massa sebab ia diproduksi secara besar-besaran berdasarkan perhitungan dagang belaka. Pencipta kebudayaan
populer hanya mencari keuntungan dari khalayak tanpa mempertimbangkan dampak baik-buruknya terhadap konsumen. Hasil kebudayaan
massa diciptakan sebagai komoditi yang berorientasi kepada produsen dalam hal laba dan bersandar pada konsumen dalam soal
cita rasa. Kedua, kebudayaan
massa itu merusak kebudayaan elit dengan cara meminjam atau mencuri atau memperalatnya. Bahkan boleh dikatakan menyedot potensi
yang ada pada kebudayaan elit. Sudah disebut sebelumnya bahwa konsumen hasil kebudayaan massa adalah rakyat kecil yang tidak
berbudaya. Bagaimanapun mereka ini ingin tampak berbudaya; oleh karenanya diperlukan berbagai unsur kebudayaan elit untuk
memberi sentuhan tertentu agar yang sifatnya massa itu menjadi istimewa. Sebagai contoh di bidang musik kita bisa mendengar
potongan lagu Beethoven disulap menjadi lagu populer yang dengan mudah bisa disebarluaskan. Di samping itu tak terhitung banyaknya
potensi artistik seniman di berbagai bidang yang dipergunakan untuk penciptaan kebudayaan massa. Berapa banyak seniman potensial
yang demi sesuap nasi telah √Ę‚¨ňdipaksa√Ę‚¨‚Ę bekerja siang malam untuk menciptakan berbagai iklan dan acara televisi murahan
di ribuan rumah produksi yang tumbuh di dunia ini. Ketiga, kebudayaan
massa menanamkan pengaruh yang sangat buruk terhadap khalayak; ingat pengaruh sex, crime, and violence yang merupakan
ciri kuat dalam kebudayaan massa. Karena orientasinya adalah cita rasa yang rendah, tema-tema yang dipilih oleh kebudayaan
massa adalah tentu saja yang mudah dicerna tanpa banyak memerlukan renungan dan acuan. Seks, kejahatan, dan kekerasan√Ę‚¨‚Ěseperti
yang sangat banyak kita dapatkan di televisi√Ę‚¨‚Ěmerupakan tema-tema pilihan utama sebab dianggap bisa langsung menarik perhatian
konsumen. Keempat, penyebarluasan
kebudayaan massa dianggap tidak hanya memerosotkan atau mengurangi nilai kebudayaan (elit) itu sendiri, tetapi juga menciptakan
khalayak yang pasif yang sangat cepat memberikan reaksi terhadap berbagai teknik godaan dan bujukan, sehingga membuat peluang
bagi munculnya totaliterisme. Dalam kaitannya dengan ini muncul pula konsep mengenai the lonely crowd √Ę‚¨ňkerumunan
orang yang kesepian√Ę‚¨‚Ę serta massa yang dengan mudah dibakar emosinya, baik untuk menuruti bujukan iklan atau hasutan penggerak
massa atau agitator politik. Karena massa sudah terbiasa menerima √Ę‚¨ňbimbingan√Ę‚¨‚Ę satu arah dari berbagai media,
dengan mudah pula mereka itu digerakkan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama seperti berdemonstrasi, mogok, dan mengadakan
perusakan meskipun sebenarnya masing-masing tidak saling mengenal. Gans membela kebudayaan
massa dengan menyatakan bahwa segala yang dituduhkan itu bisa saja dituduhkan kepada kebudayaan elit. Hasil kebudayaan elit
pun sekarang ini bisa saja diproduksi secara besar-besaran dengan maksud utama mencari keuntungan. Musik klasik, misalnya,
bisa dipergelarkan di depan ribuan pengunjung atau disiarkan televisi; bahkan bisa juga disebarluaskan lewat rekaman. Dalam
sejarah kreatifitas di Barat, dan tentunya di mana saja, seniman klasik pun suka mencuri atau meminjam berbagai unsur kebudayaan
rakyat untuk diolah dan dikembangkan sesuai dengan cita rasa si seniman dan kelompok masyarakatnya. Di samping itu, bukankah
masalah seks, kejahatan, dan kekerasan merupakan tema yang biasa beredar juga dalam kebudayaan elit? Karya sastra, drama,
dan seni rupa elit membuktikan hal tersebut. Dalam hal bimbingan kepada khalayak, tentunya kebudayaan elit pun melakukannya;
itulah justru segi didaktik yang mendasari kebudayaan elit, meskipun mungkin tidak disampaikan segampang kebudayaan massa. Dalam perkembangan
selanjutnya, pandangan pascamodernis juga menolak pemilahan gaya Matthew Arnold yang menyebut kebudayaan elit sebagai culture
dan kebudayaan massa sebagai anarchy. Pandangan itu menolak konsep wibawa lapisan elit untuk menyatakan satu-satunya
kebenaran, dan malah sebaliknya menyampaikan kenyataan bahwa yang ada ialah kebhinekaan suara dalam kebudayaan. Dalam hal
ini kesatuan suara dianggap tidak ada lagi. Di samping itu, masyarakat kita sekarang ini tidak lagi dibagi-bagi dalam lapisan-lapisan
sosial dan cita rasa yang berjenjang tetapi terdiri atas kelompok-kelompok yang memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Oleh
Gans keadaan ini disebut sebagai taste culture √Ę‚¨ňkebudayaan cita rasa.√Ę‚¨‚Ę Jika kita tidak memperhatian
alasan-alasan tersebut, masalah yang kita hadapi adalah bahwa kebudayaan massa tidak (lagi) hanya ditujukan bagi orang miskin
dan kelas bawah, tetapi untuk "kita semua"√Ę‚¨‚Ěartinya, ia dikawatirkan akan menggilas semuanya dan menjadi satu-satunya
"kebudayaan" yang menguasai semua bangsa di dunia ini. Kita sebaiknya menyadari bahwa selama ini berbagai jenis kebudayaan,
termasuk yang massa dan elit, yang asing dan daerah, tetap ada di sekitar kita. Tentu saja kita boleh memilihnya kalau mau.
Juga perlu disadari bahwa manusia bisa bergerak dari kebudayaan elit ke kebudayaan massa, bisa memilih bedhaya ketawang atau
tayuban, bisa memilih Beethoven atau Koes Plus, boleh memilih golf atau sepakbola. VII Tetapi kita tetap
saja sering mengungkapkan bahwa sastra kita berada dalam bahaya; pandangan yang berlebihan bahkan menyatakan bahwa sastra
kita akan disudutkan oleh berbagai hambatan untuk akhirnya hidup merana. Tuduhan terhadap lemahnya minat baca masyarakat sering
kita gugurkan sendiri dengan kekawatiran kita akan dominasi sastra terjemahan yang mengalami kemajuan yang pesat akhir-akhir
ini. Sebenarnya kekawatiran itu tidak perlu ada sebab sejarah telah mencatat juga dominasi sastra terjemahan dalam kehidupan
nenek-moyang kita; dengan sangat cekatan kita bahkan telah menyadur sastra asing dan menjadikannya bagian penting yang ikut
mengembangkan kebudayaan kita. Sastra asing yang
telah diterjemahkan tidak lagi menjadi milik bahasa dan kebudayaan sumbernya, tetapi merupakan bagian tak terpisahkan dari
bahasa dan kebudayaan sasarannya. Dengan demikian maka Arjuna, Abunawas, dan Pinokio adalah para tetangga kita yang sudah
kita lupakan asal-usulnya. Mungkin pada awalnya dulu kita tertarik kepada tokoh-tokoh itu justru karena mereka menghadirkan
hal penting yang tidak hadir dalam kehidupan kita. Keasingan itulah yang menjadikan mereka itu "hidup" dalam kehidupan sehari-hari
kita. Ditinjau dari sudut pandang ini, kegiatan penerjemahan sastra sekarang ini sebaiknya tidak ditanggapi sebagai ancaman
kehidupan sastra kita, tetapi justru harus kita syukuri sebagai hal yang memberikan sumbangan bagi pemenuhan kehendak kuat
kita untuk mendapatkan akses ke berbagai hal yang tidak bisa kita dapatkan. Sastra, dalam zaman
kita ini, telah menjadi barang dagangan. Penerbit adalah perusahaan yang dalam kegiatannya harus selalu memperhitungkan untung-rugi.
Tampaknya, dalam perhitungan itu menerbitkan karya terjemahan lebih menguntungkan daripada menerbitkan karya asli. Karya sastra
asing yang siap diterjemahkan tidak terhitung jumlahnya, dan kita semua tahu bahwa proses menerjemahkan tentu lebih sederhana
daripada proses menciptakan karya asli. Di samping itu jaminan lakunya karya sastra tampaknya lebih pasti sebab tidak jarang
ditunjang oleh iklan mengenai keberhasilannya di luar negeri dan pemunculannya dalam bentuk kesenian lain, terutama film. Kita juga sering mengeluh
mengapa kita tidak mampu menghasilkan karya sastra yang, tidak usah adikarya, tetapi cermat, kokoh, dan padu seperti yang
sering kita jumpai dalam sastra terjemahan. Dalam hal ini kita harus memperhatikan dua sistem yang berkaitan dengan kelahiran
karya sastra, yakni kepengarangan dan penerbitan. Sastrawan kita umumnya bekerja sendirian; ia harus bekerja secepat-cepatnya
tanpa bantuan orang lain untuk memeriksa karangannya. Umumnya sastrawan kita memiliki kerja rangkap, artinya ia tidak bisa
mempergunakan seluruh waktunya hanya untuk mengarang. Kesan kuat yang kita dapatkan dari kebanyakan karya sastra kita adalah
penulisannya yang sangat tergesa-gesa. Perkembangan sastra
kita banyak ditaja oleh penyelenggaraan berbagai sayembara penulisan. Saya curiga kebanyakan naskah yang masuk dalam sayembara
itu ditulis dengan sangat tergesa-gesa; sebuah novelette mungkin ditulis satu atau dua minggu sebelum dikirimkan; hampir tidak
ada tanda-tanda bahwa kebanyakan naskah itu penah diperiksa ulang oleh penulisnya. Di lain pihak, penerbit juga tidak memiliki
banyak waktu√Ę‚¨‚Ědi samping juga tidak memiliki kemampuan cukup√Ę‚¨‚Ěuntuk menyuntingnya. Penerbit koran, majalah, atau buku
di negeri ini tampaknya benar-benar menyadari pentingnya gerak cepat dalam mengumpulkan laba sebanyak-banyaknya. Di dalam
sistemnya, hampir tidak disediakan ruang untuk kemampuan yang benar-benar handal dalam penyuntingan. Sastra bukan kitab suci
yang tidak bisa disunting agar menjadi lebih baik; sastrawan bukan nabi yang menyampaikan Sabda. Sastrawan hanyalah manusia
biasa yang berusaha menciptakan benda budaya yang, tentu saja, bisa mengandung cacat yang bisa diperbaiki pihak lain. Dalam hal ini proses
penulisan novel John Grisham bisa dijadikan sekedar contoh. Ia adalah novelis yang memberi kesan bahwa novel-novelnya ditulis
berdasarkan "penelitian" yang cermat atas masalah yang ditulisnya, mungkin justru karena itu ia tidak menulis tergesa-gesa
dan sekali jadi. Mungkin saja novel-novelnya sebenarnya tidak merupakan hasil kerja sendirian; ada editor yang membantu melahirkan
novelnya. Konon, novelnya The Rainmaker yang hak ciptanya untuk film bisa mencapai 16 milyar rupiah, mula-mula terdiri
atas sekitar 750 halaman yang kemudian dirampingkan menjadi 434 halaman saja.9 Perampingan itu bisa saja dilakukan olehnya
sendiri, bisa juga oleh pasukan penyunting yang benar-benar mampu melakukan tugasnya. Harus kita akui bahwa
sepandai-pandainya pengarang, bisa saja ia melakukan kekeliruan atau kecerobohan dalam cara penyampaian maupun apa yang disampaikan.
Ia mempunyai kewajiban untuk memeriksa ulang dan memperbaikinya, dan penerbit yang baik juga berkewajiban untuk membantunya.
Naskah yang masuk ke penerbit dan penyelenggara sayembara penulisan menunjukkan bahwa kecerobohan pengarang sangat tiggi kadarnya.
Menurut pengalaman saya, praktis tidak pernah ada naskah peserta sayembara penulisan yang seratus persen siap untuk diterbitkan.
Karena tidak adanya usaha untuk menyelenggarakan penyuntingan yang sungguh-sungguh, sebenarnya sebagian besar sastra kita
adalah sastra yang ceroboh. Kita pernah membaca kritik F. Rahardi, penyair dan redaktur majalah pertanian Trubus, terhadap
kecerobohan A. Tohari mengenai berbagai masalah pertanian dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk.10 Novel Umar Kayam yang
banyak mengandung kosa kata Jawa, Para Priyayi, agak menderita sebab tampaknya si penyunting tidak begitu menguasai
penulisan ejaan bahasa Jawa. Dan amat sangat banyak karya sastra kita yang mencerminkan lemahnya penguasaan bahasa; cerita
rekaan menjadi bertele-tele dan menjengkelkan, puisi menjadi gelap. Sastra tidak bisa
dilahirkan dengan tergesa-gesa, pengarang tidak bisa sepenuhnya bekerja sendirian√Ę‚¨‚Ěia langsung atau tak langsung memerlukan
bantuan bidang dan keahlian lain. Sistem kesusastraan kita tampaknya belum sepenuhnya siap menunjang kelahiran sastra di zaman
yang serba cepat ini. Bisnis penerbitan mensyaratkan dipercepatnya proses penerbitan dan dilipatgandakannya judul buku baru.
Tujuan penerbitan yang mementingkan faktor laba ini segera tampak bertentangan dengan hakikat sastra yang memang tidak bisa
dipaksa tergesa-gesa dan ceroboh. Yang sekarang diperlukan adalah suatu sistem penerbitan sastra yang bisa mempertemukan keduanya.
Jadi, kita harus menciptakan sistem kepengarangan dan penerbitan yang bisa bekerja sama dengan baik, tanpa harus merugikan
perkembangan kesusastraan.***
|
|||||||||||
|
Enter content here |
|||||||||||
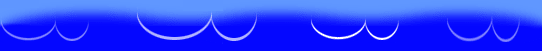 |
|||||||||||
|
Enter supporting content here
|
|||||||||||